ACTANEWS.CO.ID – OPINI, Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menguji kesiapan negara dalam menangani krisis ekologis yang berdimensi sosial, politik, dan hukum. Skala kerusakan lintas wilayah, melibatkan ribuan pengungsi, kerusakan infrastruktur vital, dan gangguan aktivitas ekonomi, menempatkan negara pada titik krusial untuk menentukan apakah peristiwa ini cukup memenuhi syarat sebagai bencana nasional sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Pertanyaan tersebut tidak hanya teknis administratif, tetapi merupakan pertanyaan moral dan yuridis tentang sejauh mana negara menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas.
Dalam hukum nasional, penetapan status bencana diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini membedakan bencana berskala daerah, provinsi, dan nasional, yang penetapannya mempertimbangkan tiga parameter utama: jumlah korban dan kerusakan, cakupan wilayah, serta kemampuan daerah dalam menangani situasi. Pasal 7 jo. Pasal 51 UU 24/2007 menegaskan bahwa ketika kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai untuk menangani kondisi darurat, maka pemerintah pusat melalui Presiden dapat menetapkan status bencana nasional.
Disisi lain, diskursus akademik juga memperlihatkan kehati-hatian. Beberapa ahli kebencanaan, seperti Syamsul Maarif (mantan Kepala BNPB), pernah mengingatkan bahwa penetapan bencana nasional harus mempertimbangkan konsekuensi logistik, keuangan, dan tata kelola. Status ini akan mengalihkan seluruh komando kepada pemerintah pusat dan membuka keran penggunaan anggaran kontinjensi nasional. Namun, kehati-hatian tidak boleh berujung pada stagnasi. Jika indikator objektif menunjukkan bahwa daerah kewalahan, maka menunda penetapan bencana nasional justru bertentangan dengan prinsip perlindungan warga negara.
Sudut pandang politik dan administrasi publik, penetapan bencana nasional sering diinterpretasikan sebagai indikator kegagalan daerah dalam mitigasi dan respons awal. Beberapa kepala daerah dan akademisi kebijakan publik melihat hal ini sebagai potensi masalah dalam hubungan pusat dan daerah. Namun, pendekatan demikian terlalu mengedepankan sensitivitas politis daripada urgensi kemanusiaan. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pun memungkinkan adanya intervensi pusat pada situasi tertentu demi menjaga pelayanan dasar, termasuk keselamatan warga.
Jika melihat parameter empiris pada bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar apabila kerusakan meluas, akses terputus, ribuan rumah terdampak, hingga beberapa titik menyatakan tanggap darurat, maka terdapat argumentasi kuat bahwa bencana ini memiliki karakter lintas kapasitas daerah. Dalam konsepsi hukum administrasi, keputusan Presiden tentang status bencana nasional merupakan diskresi konstitusional yang harus didasarkan pada asas proporsionalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi, khususnya hak untuk hidup dan rasa aman (Pasal 28A dan 28G UUD 1945).
Mengutip perkataan Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya fungsi emergency power yang digunakan secara terukur ketika negara menghadapi keadaan luar biasa. Menurutnya, alasan kemanusiaan adalah justifikasi paling kuat untuk memperluas peran eksekutif dalam pengelolaan krisis. Sementara itu, pandangan pakar lingkungan seperti Prof. Sudharto P. Hadi menyoroti bahwa penanganan bencana lintas provinsi membutuhkan komando nasional agar mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi dapat berjalan terpadu.
Adapun kekurangan penetapan bencana nasional tetap perlu dicatat. Status ini berpotensi menyebabkan ketergantungan daerah kepada pusat, mengurangi fleksibilitas pemerintahan lokal, dan menimbulkan tekanan besar pada APBN. Namun, kekurangan tersebut tidak dapat disamakan dengan hambatan yuridis. UU 24/2007 telah memberikan landasan kuat bagi negara untuk mengambil alih komando tanpa menghilangkan peran daerah.
Pada kondisi saat ini, yang dibutuhkan bukan polemik formal, melainkan keberanian mengambil keputusan berbasis bukti dan prinsip konstitusional. Menetapkan bencana sebagai bencana nasional atau tidak, pada akhirnya bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penanganan, pemulihan, dan pencegahan jangka panjang berjalan optimal. Negara tidak boleh hadir setengah hati ketika warganya menghadapi ancaman yang menggerogoti hidup, ruang tinggal, dan masa depan mereka. Sebagai konklusi dalam menghadapi bencana besar seperti yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, prinsip (salus populi suprema lex esto) keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka harus ditempatkan sebagai asas utama. Ketika keselamatan rakyat terancam secara masif dan lintas wilayah, maka seluruh pertimbangan fiskal, politik, dan citra pasar harus ditempatkan di bawah prinsip tersebut. Kehati-hatian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengalahkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga dalam situasi darurat. Dalam hal ini status bencana nasional diperlukan atau tidak, seharusnya ditentukan oleh kebutuhan rakyat, bukan kalkulasi politik. Jika keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka tidak ada alasan yuridis yang cukup kuat untuk menahan keputusan tersebut. (GG)
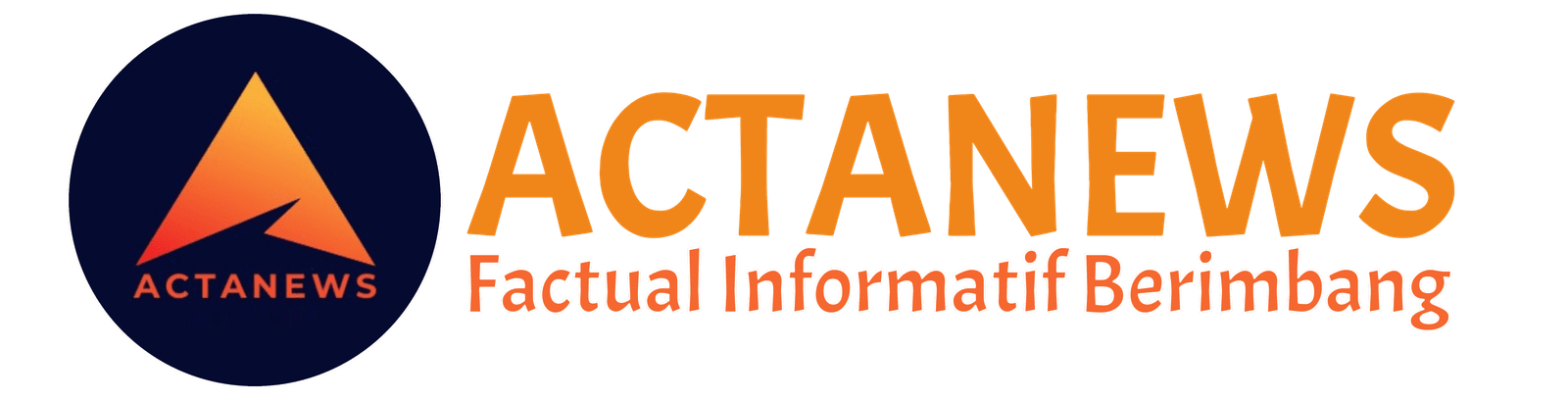







Leave a Reply